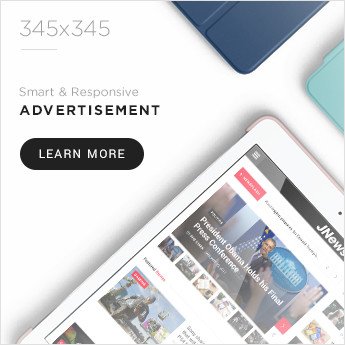SAIBETIK– Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2025 dipastikan berlangsung panas. Sebanyak 25 ribu petani dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi serentak menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria yang telah berlangsung puluhan tahun. Di ibu kota, sekitar 12 ribu petani bergerak menuju Gedung DPR RI, sementara 13 ribu lainnya menggelar aksi solidaritas di sejumlah kota besar seperti Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, hingga Manado.
Aksi besar ini digelar bertepatan dengan peringatan 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Alih-alih berhasil menyejahterakan petani, UUPA justru dinilai gagal dijalankan lintas rezim. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, aksi tahun ini membawa sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural agraria yang semakin memperburuk kehidupan petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
“Selama 65 tahun, reforma agraria hanya jadi janji kosong. Dari masa ke masa, petani terus menghadapi konflik tanah, ketimpangan penguasaan lahan, hingga kriminalisasi. Melalui aksi ini kami menuntut negara hadir dengan solusi nyata, bukan hanya rapat demi rapat,” ujar Dewi Kartika dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/9).
Gelombang massa di Jakarta didominasi petani dari Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Mereka tergabung dalam Serikat Petani Pasundan dari lima kabupaten (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran), Serikat Petani Majalengka, Serikat Pekerja Tani Karawang, Pemersatu Petani Cianjur, Paguyuban Petani Suryakencana Sukabumi, hingga Pergerakan Petani Banten.
Di tengah aksi, Abay Haetami, Ketua Pergerakan Petani Banten (P2B), menyoroti maraknya konflik tanah di wilayah Banten. Ia menuturkan, banyak petani dipaksa kehilangan lahan dengan dalih ketahanan pangan. Pohon dan tanaman produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dirusak, lalu diganti dengan proyek jagung yang justru menguntungkan korporasi besar. “Petani kita dirugikan, tanah mereka dirampas, bahkan nelayan di Ujung Kulon tak bisa lagi berlabuh hanya karena dituduh pencuri,” kata Abay.
Sementara itu, generasi muda petani juga ambil bagian dalam aksi. May Putri Evitasari dari Paguyuban Petani Aryo Blitar menegaskan bahwa tuntutan reforma agraria bukan hanya untuk orang tua mereka, tetapi juga untuk masa depan anak-anak petani. “Kami sulit mengakses pendidikan dan pekerjaan layak karena tanah warisan orang tua sudah tak ada lagi. Akhirnya banyak yang terpaksa jadi buruh migran, padahal kami ingin tetap bekerja di desa,” tegasnya.
Senada, Rangga Wijaya dari Serikat Pekerja Tani Karawang (Sepetak) menyesalkan nasib lumbung padi nasional yang kini berubah menjadi lahan industri. “Dulu Karawang dikenal sebagai pusat produksi beras, kini sawah-sawah hilang, petani tersingkir, dan lahan subur jadi proyek investasi,” ujarnya.
Dhio Dhani Shineba, anggota Dewan Nasional KPA, menambahkan bahwa pola represif aparat semakin marak terjadi. “Selama 31 tahun kami mendampingi petani, tren kekerasan dari aparat justru meningkat. Setiap tahun, janji reforma agraria ditagih, tapi jawabannya selalu nihil,” katanya.
Kegagalan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi sorotan utama. Dibentuk sejak era pemerintahan Jokowi, lembaga ini dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata. Ketimpangan lahan justru semakin parah. Data KPA menyebutkan, satu persen kelompok elit menguasai 58 persen tanah dan sumber daya alam Indonesia, sedangkan 99 persen rakyat berebut sisanya.
Akibat ketidakadilan tersebut, sepanjang 2015–2024 terjadi sedikitnya 3.234 konflik agraria dengan luas mencapai 7,4 juta hektare. Dampaknya, sekitar 1,8 juta keluarga kehilangan tanah, penghidupan, dan masa depan. “Ini bukan sekadar angka. Setiap konflik berarti ada keluarga yang terusir, anak yang kehilangan kesempatan sekolah, dan petani yang kehilangan harapan,” ungkap Dewi.
Selain karena lemahnya implementasi reforma agraria, konflik juga diperparah oleh proyek-proyek investasi berskala besar. Program food estate, Proyek Strategis Nasional (PSN), bank tanah, hingga kawasan ekonomi khusus disebut sebagai biang kerok perampasan tanah rakyat. “Proyek-proyek itu diklaim untuk kesejahteraan rakyat, tapi faktanya justru merampas hak petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan desa,” tambah Dewi.
KPA menegaskan bahwa baik pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan saat ini di bawah Presiden Prabowo telah gagal menjalankan amanat UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945. Bagi petani, aksi ini adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga sumber kehidupan dan identitas.***