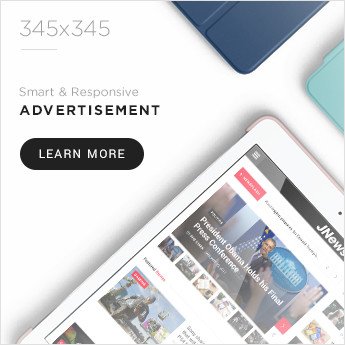SAIBETIK— Panitia Puisi Peduli Bencana Sumatera 2025 mengumumkan 118 puisi yang lolos kurasi dan akan dimuat dalam buku Tanda Cinta bagi Korban Bencana Sumatera, Rabu (16/12/2025). Buku ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap banjir dan longsor besar yang melanda berbagai wilayah Sumatera pada penghujung 2025, sebuah tragedi yang merenggut ratusan nyawa dan memaksa hampir satu juta orang mengungsi dari rumah mereka.
Buku ini bukan sekadar antologi puisi bertema bencana. Mustafa Ismail, salah satu pemrakarsa sekaligus jurnalis dan penyair dari Aceh, menekankan bahwa karya-karya dalam buku ini merupakan bentuk kesaksian moral dan etis. “Puisi-puisi di dalamnya bukan sekadar ungkapan empati, melainkan bentuk kesaksian kolektif atas bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah Sumatera pada akhir 2025,” katanya. Kesaksian ini hadir sebagai refleksi yang menegaskan bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor ekologis, sosial, dan kebijakan manusia.
Keragaman penyair yang terlibat juga menjadi keistimewaan buku ini. Penyair berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Turki. Hal ini menunjukkan bahwa duka Sumatera tidak berdiri sendiri, tetapi beresonansi secara internasional. Mustafa menambahkan bahwa keberadaan penyair lintas negara ini menjadikan buku sebagai ruang dialog global yang menghubungkan pengalaman lokal dengan keprihatinan dunia.
Secara tematik, puisi-puisi dalam buku ini menolak pandangan bahwa bencana adalah peristiwa alam yang netral. Dedy Tri Riyadi, kurator kegiatan ini, menjelaskan, “Bencana tidak diperlakukan sebagai peristiwa alam yang netral, melainkan sebagai simpul pertemuan antara hujan ekstrem, kerusakan lingkungan, kelalaian manusia, dan ketimpangan kuasa.” Dari puisi pembuka, Arus Deras Itu karya Ahmadun Yosi Herfanda, hingga Variabel Liar Persamaan karya Rintis Mulya, pembaca disuguhi refleksi tentang kehancuran ekologis dan sosial yang tak terpisahkan dari tindakan manusia.
Puisi-puisi lain juga menyoroti dampak sosial dan kultural bencana. Misalnya, Sobekan Perca Tanah Gayo karya Fikar W. Eda menghadirkan longsor dan banjir sebagai peristiwa yang memutus sejarah, budaya, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan. Sementara puisi Isbedy Stiawan ZS, Jangan Tahan Tubuhku, mempersonifikasikan air sebagai entitas yang dilepaskan manusia sendiri setelah penebangan hutan dan pengrusakan ekosistem. Dimensi kehilangan spiritual dan personal juga muncul dalam karya Nanang R. Supriyatin, November Rain, dan Riri Satria, Doa untuk Kampung Halaman, yang menampilkan kisah anak, ibu, dan kampung yang kehilangan, serta doa sebagai jembatan antara yang selamat dan yang hilang.
Nada kritik terhadap kebijakan pemerintah juga muncul, seperti pada puisi Kurnia Effendi, yang secara terang menyebut izin dan kebijakan sebagai bagian dari masalah ekologis. Triyanto Triwikromo dalam Hanyut menggambarkan negara dan parlemen ikut hanyut, meninggalkan rakyat di atap rumah yang terendam. Melalui karya-karya ini, puisi menjadi medium untuk menuntut tanggung jawab dan kesadaran kolektif.
Iwan Kurniawan, jurnalis Tempo dan penggagas kegiatan ini, menegaskan, “Puisi-puisi itu menjadi tanda cinta bukan dalam arti romantik, melainkan keberanian untuk menyebut luka, menunjuk sebab, dan menolak lupa.” Buku Tanda Cinta bagi Korban Bencana Sumatera dijadwalkan terbit Desember 2025 oleh Ruang Merdeka Inspira. Peluncurannya akan digelar di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin pada 19 Desember 2025 melalui acara Panggung Puisi Bencana Sumatera, yang akan menampilkan pembacaan puisi, testimoni penyintas, dan penggalangan donasi untuk korban. Buku ini diharapkan menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang sering memadatkan bencana menjadi statistik, puisi mampu mengembalikan wajah, suara, dan identitas manusia yang terdampak.***