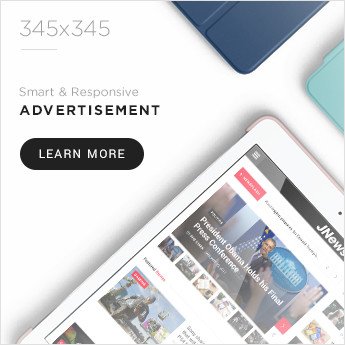Kiagus Bambang Utoyo
SAIBETIK – Di tengah jargon efisiensi yang terus digaungkan dari podium-podium pemerintahan, rakyat justru bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan? Saat angka-angka penghematan dijadikan tolak ukur keberhasilan, masyarakat di lapisan bawah masih harus menakar belanja harian dengan kecemasan, seperti menghitung tetes terakhir bensin di tengah jalan sunyi.
Efisiensi anggaran sering disampaikan dalam nada heroik—dengan presentasi, grafik, dan janji perubahan. Namun bagi rakyat kecil, efisiensi bukan lagi soal statistik. Ia hadir dalam bentuk harga sembako yang tak kunjung bersahabat, infrastruktur yang tertunda, dan pelayanan publik yang kerap hanya menjadi wacana.
Jika dijalankan secara benar, efisiensi tentu berbuah manis: anggaran tak lagi bocor, program pemerintah tepat sasaran, dan rakyat merasakan langsung manfaatnya. Dana perjalanan dinas bisa dialihkan ke sekolah, puskesmas, atau irigasi pertanian. Sayangnya, kenyataan tak selalu seindah teori. Ketika inflasi dikendalikan hanya di layar komputer, bukan di warung dan pasar, efisiensi justru menjauhkan negara dari dapur rakyat.
Kesenjangan kian terasa saat penghematan dibebankan ke rakyat, sementara elite birokrasi justru menikmati tunjangan dan fasilitas negara yang terus membengkak. Rakyat diminta berhemat, namun pejabat menikmati gaya hidup yang sulit dijangkau logika keadilan sosial. Di saat pedagang kecil berjuang menutup utang, sebagian BUMN dikelola seperti milik pribadi dengan bonus miliaran rupiah.
Lebih dari itu, efisiensi sejati juga ditantang oleh resistensi internal birokrasi. Pemangkasan honor rapat, pembatasan perjalanan dinas, hingga penghapusan lembur otomatis, dianggap mengusik kenyamanan lama. Maka lahirlah perlawanan halus: prosedur diperlambat, kebijakan dipersulit, dan pemborosan berganti wajah.
Kritik juga diarahkan pada kerja sama luar negeri yang kerap melemahkan kedaulatan ekonomi. Sumber daya strategis dijadikan barang tukar, utang luar negeri terus menumpuk, dan akademisi lokal belum menjadi kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan nasional. Efisiensi pun kehilangan makna jika tak diiringi dengan kualitas SDM yang kuat dan visi kebangsaan yang jelas.
Pada akhirnya, esensi efisiensi anggaran seharusnya bukan sekadar penghematan, melainkan perlindungan terhadap hak dasar rakyat: makan cukup, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Inilah bentuk cinta negara yang paling nyata.
Pertanyaannya kini: apakah efisiensi anggaran kita benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk menciptakan narasi indah di laporan tahunan?***