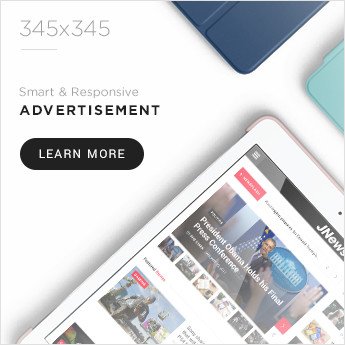SAIBETIK— Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah bencana alam di Indonesia. Lebih dari 800 orang dinyatakan meninggal dunia dan sekitar 500 lainnya masih hilang. Ribuan rumah luluh lantak, ratusan fasilitas umum rusak, sementara akses jalan di puluhan kabupaten terputus total. Situasi ini memicu krisis kemanusiaan besar-besaran yang membuat ribuan warga mengungsi dan membutuhkan bantuan mendesak.
Bencana ini dipicu oleh cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, namun para ahli menilai kerusakan ekologis jangka panjang di Sumatera menjadi faktor utama yang memperburuk dampak banjir dan longsor. Kawasan hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebut mengalami degradasi hebat, membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan meningkatkan risiko banjir bandang.
Edy Karizal, Direktur Lembaga Konservasi 21 (LK-21), menegaskan bahwa kondisi ekosistem yang melemah sudah lama menjadi bom waktu. “Curah hujan ekstrem memang tidak terhindarkan, tapi ekosistem yang rusak memperburuk keadaan. Hulu yang kehilangan tutupan hutan membuat aliran air dan material longsoran tidak tertahan,” ujarnya kepada pesawaran.pikiran-rakyat.com, Minggu (7/12/2025).
Data yang diungkap LK-21 menunjukkan betapa masifnya alih fungsi hutan dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan sekitar 1,64 juta hektare hutan di berbagai provinsi telah berubah menjadi Area Peruntukan Lain (APL). Aceh kehilangan sekitar 70.000 hektare, Sumut 150.000 hektare, Riau 600.000 hektare, Jambi 120.000 hektare, Kalbar 60.000 hektare, Kalteng 350.000 hektare, Kaltim 250.000 hektare, dan wilayah lain sekitar 50.000 hektare.
Menurut Edy, hilangnya tutupan hutan membuat longsor membawa gelondongan kayu dan lumpur ke pemukiman. “Ini bukan sekadar bencana alam. Ini dampak dari melemahnya perlindungan lingkungan selama bertahun-tahun,” ujarnya. Ia juga menilai beberapa regulasi terbaru perlu dievaluasi, termasuk kebijakan yang memberi ruang konversi kawasan konservasi melalui Permen LHK Nomor 14 Tahun 2023.
Selain memicu bencana hidrometeorologi, hilangnya tutupan hutan juga mengancam satwa endemik Sumatera seperti harimau, gajah, badak, dan orangutan. Konflik satwa–manusia disebut meningkat dalam satu dekade terakhir, dipicu oleh berkurangnya habitat alami dan meningkatnya aktivitas manusia di kawasan konservasi.
Edy menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap kebijakan lahan dan izin perkebunan. “Hutan alam berbeda dari perkebunan monokultur. Mengganti hutan dengan sawit tidak serta-merta menjaga fungsi ekologisnya,” ujarnya. Penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan menurutnya masih sangat lemah, sehingga memberi ruang bagi praktik alih fungsi lahan tanpa kontrol.
Ia juga mendorong investigasi terbuka penyebab kerusakan lingkungan. “Kalau memang ada kebijakan yang memperburuk kondisi ekologis, harus dievaluasi melalui mekanisme hukum dan audit yang kredibel. Semua pihak harus ikut terlibat, termasuk lembaga independen dan masyarakat,” tegasnya.
Respons Pemerintah
Pemerintah pusat menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah evakuasi korban, pencarian orang hilang, dan penyaluran bantuan logistik. Beberapa kementerian telah menyiapkan rencana pemulihan jangka menengah dan panjang untuk wilayah terdampak, termasuk normalisasi sungai, rehabilitasi fasilitas umum, hingga relokasi warga dari zona rawan.
Namun para ahli menilai bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Bencana ini menjadi alarm keras bahwa integrasi kebijakan lingkungan, tata ruang berbasis risiko, dan mitigasi bencana harus diperkuat. Tanpa koreksi kebijakan dan perlindungan ekosistem hulu, risiko bencana serupa akan semakin tinggi.
Banjir Sumatera 2025 menjadi pengingat bahwa ketika hutan kehilangan fungsi alaminya, masyarakat berada dalam ancaman. Penguatan perlindungan lingkungan, haluan pembangunan berkelanjutan, dan rehabilitasi kawasan kritis harus menjadi prioritas untuk mencegah korban jiwa yang lebih besar di masa depan.***