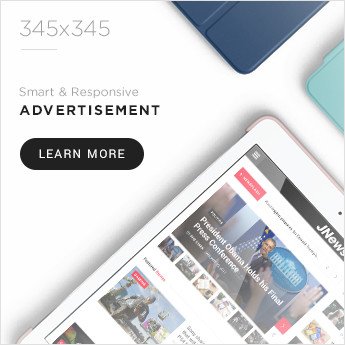SAIBETIK- Indonesia kerap menyebut diri sebagai “surga investasi.” Namun realitas di lapangan jauh dari klaim tersebut. Regulasi tumpang tindih, izin berlapis, serta ketidakpastian hukum justru menjadikan negeri ini ladang penuh risiko. Investor, yang mencari kepastian, memilih hengkang ke Vietnam, Thailand, atau Malaysia—negara dengan aturan jelas, birokrasi ramping, dan iklim usaha yang kondusif.
Akibatnya, Indonesia hanya kebagian remah investasi. Pertumbuhan ekonomi melambat, lapangan kerja berkurang, dan daya saing menurun. Regulasi yang seharusnya menjadi pondasi pembangunan malah berubah menjadi tembok penghalang.
Kisah Bumi Dipasena di Lampung menjadi cermin nyata. Tambak udang seluas 16 ribu hektare yang pada 1990-an menyumbang devisa miliaran rupiah, kini merana. Sejak 2021, wacana revitalisasi tak pernah beranjak dari meja rapat. Infrastruktur rusak, teknologi tertinggal, sementara petambak kecil bertahan dengan gotong royong dan iuran Rp1.000 per kilogram panen untuk membangun kemandirian.
Ironisnya, pemerintah justru hadir sebatas kajian dan dokumen. Seolah lupa, bahwa Dipasena menyimpan luka lama: kemitraan timpang, konflik berkepanjangan, dan petambak yang terpinggirkan di tanah sendiri. Hari ini, mereka memilih jalan kemandirian—model sederhana, adil, dan berpihak pada rakyat.
Revitalisasi Dipasena adalah ujian bagi negara. Apakah benar-benar hadir untuk rakyat, atau hanya piawai melontarkan janji? Jika berani melangkah ke implementasi nyata, Dipasena bisa kembali jadi ikon perikanan dunia, mengangkat devisa sekaligus kesejahteraan pesisir. Tapi jika tidak, ia hanya akan menjadi monumen kegagalan: simbol bagaimana regulasi berbelit lebih diprioritaskan daripada masa depan rakyat.
Investor boleh pergi, modal asing boleh berpindah. Namun pertanyaan mendasarnya: untuk siapa sebenarnya regulasi itu dibuat, bila rakyat sendiri justru tersisihkan?
— Suseno, Direktur Utama PT Sakti Biru Indonesia.***