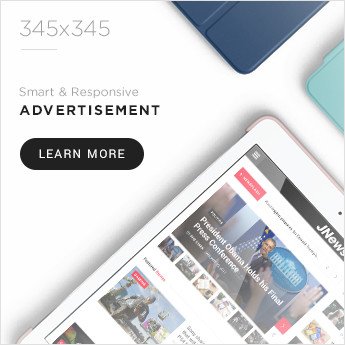SAIBETIK- Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI menjadi titik hitam dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Tragedi ini bukan sekadar catatan kelam, melainkan peringatan nyata betapa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bisa mengancam persatuan bangsa. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu menelan korban tujuh jenderal terbaik negeri ini yang gugur secara tragis. Sejak saat itu, PKI dinyatakan terlarang, dan ideologi komunisme dipandang sebagai ancaman yang tak boleh kembali berakar di Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa kemarahan rakyat, dukungan TNI, serta gerakan ormas Islam menjadi faktor kunci yang menumpas pemberontakan tersebut. Orde Baru kemudian menegaskan pelarangan komunisme demi menjaga bangsa dari jurang pengkhianatan yang sama. Namun, perdebatan tentang G30S/PKI tidak pernah benar-benar surut. Banyak sejarawan dan pengamat politik menilai ada campur tangan asing dalam tragedi itu, dengan tujuan mengguncang kekuasaan Presiden Sukarno. Apa pun versinya, satu hal yang jelas: bangsa Indonesia tidak boleh lupa, apalagi lengah.
Bahaya laten komunisme tetap menjadi isu sensitif. Setiap upaya penyusupan ideologi asing, baik secara langsung maupun terselubung, bisa menjadi pintu masuk bagi keretakan bangsa. Hal ini menjadi semakin relevan ketika gejolak politik di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mulai terasa. Istilah “Agustus Kelam 2025” menjadi simbol kegelisahan publik, khususnya generasi muda yang mendambakan Indonesia Emas 2045. Mereka khawatir kepentingan politik jangka pendek dan kompromi kekuasaan justru membuka ruang bagi masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Isu lain yang memicu kekhawatiran adalah munculnya sejumlah tokoh dengan latar belakang kontroversial yang kini menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan BUMN. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik: apakah bangsa ini benar-benar sudah belajar dari sejarah, atau sedang mengulang kesalahan yang sama?
Pemerintahan Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Keterbukaan politik memang penting, tetapi jangan sampai semangat merangkul justru menjadi celah bagi infiltrasi. Pancasila harus tetap ditempatkan sebagai fondasi, bukan sekadar simbol yang dipajang dalam pidato. Setiap kebijakan negara wajib berpijak pada kepentingan rakyat, bukan pada agenda asing, bukan pula pada ideologi yang pernah gagal menjaga persatuan bangsa.
Tragedi G30S/PKI 1965 bukan sekadar lembaran sejarah, tetapi peringatan keras yang relevan hingga hari ini. Bangsa ini harus terus waspada, generasi muda harus paham sejarah, dan pemerintah harus konsisten menegakkan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo dihadapkan pada ujian besar: apakah ia mampu memastikan bahwa semangat persatuan benar-benar merangkul seluruh rakyat Indonesia secara adil, tanpa membuka celah bagi ideologi yang dapat mengancam keberlangsungan republik.***