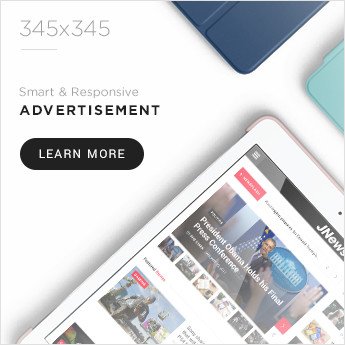SAIBETIK– Dunia sastra kembali bergetar dengan lahirnya karya berjudul “Tangis Sekolah Hantu Wali Kota” dari penyair muda, Alfariezie. Tulisan ini bukan sekadar puisi, melainkan sebuah ledakan satire politik yang mengguncang kesadaran publik tentang carut-marut pendidikan di daerah, khususnya soal praktik sekolah ilegal yang justru mendapat kucuran dana pemerintah.
Puisi yang ditulis dengan gaya metaforis itu menampilkan jeritan batin para orang tua murid yang terjebak dalam paradoks kebijakan pemerintah. Alih-alih memberikan kepastian hukum dan mutu pendidikan, sekolah ilegal yang difasilitasi justru mengancam masa depan anak-anak dengan “mendung putih”, metafora untuk pupusnya harapan.
Tema yang diangkat Alfariezie sangat relevan: protes terhadap penyelenggaraan sekolah tanpa izin resmi. Kritik diarahkan langsung pada Wali Kota Bandar Lampung sebagai simbol penguasa yang dianggap melegitimasi praktik berbahaya ini. Melalui kata-kata tajam, penulis seolah ingin membuka mata publik bahwa kebijakan pendidikan yang sembrono dapat melahirkan generasi korban.
Gaya bahasa yang digunakan brutal, liar, sekaligus penuh sindiran. Simbol-simbol hewan buas seperti babi hutan, macan, hingga buaya dipakai untuk menggambarkan kerakusan dan kebengisan para aktor yang terlibat. Misalnya dalam larik “Kepala sekolah bisa babi hutan terembat macan,” tersirat pesan tentang predatorisme dalam birokrasi pendidikan. Sementara ungkapan “pejabat kelas bawah layaknya buaya terjerat keluarga korban” menyajikan ironi: pejabat yang mestinya melindungi justru terperangkap dalam lingkaran masalah.
Lebih jauh, Alfariezie menggunakan bentuk puisi bebas dengan pemenggalan baris yang ritmis. Seruan “Bahaya!” di tengah puisi memberi efek agitasi, seakan pembaca sedang disuguhi orasi politik, bukan sekadar karya sastra. Pendekatan ini membuat puisi menjadi senjata kritik sosial, membangkitkan emosi dan mendorong aksi reflektif dari publik.
Nilai estetiknya terletak pada keberanian memadukan realitas sosial dengan alegori sastra. Penulis tidak menyebut nama sekolah atau pejabat secara eksplisit, melainkan membungkus kritiknya dalam simbol-simbol puitis. Cara ini menghadirkan ruang interpretasi luas sekaligus menjaga posisi karya sebagai bagian dari tradisi sastra protes yang kuat di Indonesia.
Relevansi karya ini sangat besar. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi masalah tata kelola pendidikan, keberadaan “sekolah hantu” menjadi fenomena nyata. Gedung berdiri tanpa izin, murid diterima tanpa kepastian ijazah, namun dana tetap mengalir dari pemerintah. Kritik Alfariezie ibarat alarm yang mengingatkan: bila dibiarkan, korban terbesarnya adalah generasi penerus bangsa yang kehilangan hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan legal.
“Tangis Sekolah Hantu Wali Kota” pada akhirnya bukan sekadar puisi, melainkan manifestasi keresahan sosial. Ia menjembatani seni dan jurnalisme protes, memadukan estetika bahasa dengan urgensi kritik. Meski bagi sebagian pembaca metafora-metafora liar ini mungkin membingungkan, justru di situlah letak kekuatan karyanya—memaksa audiens untuk berpikir lebih dalam tentang makna di balik simbol.
Karya ini sekaligus memperlihatkan bahwa suara penyair muda tidak bisa diremehkan. Mereka mampu menyuarakan kritik sosial dengan cara berbeda, menyalakan kesadaran publik lewat seni. Alfariezie menunjukkan bahwa puisi bisa menjadi senjata politik yang lebih tajam daripada pidato panjang di podium.***