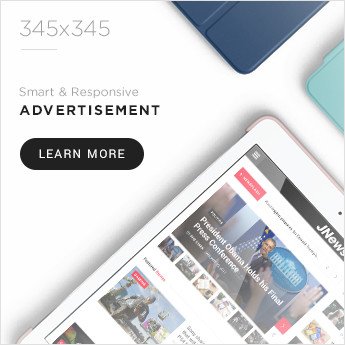SAIBETIK- Seorang ibu idealnya menjadi simbol perlindungan, kebijaksanaan, dan keberpihakan pada masa depan anak-anaknya. Namun ketika kekuasaan bertemu kepentingan, figur ibu justru bisa berubah menjadi metafora kegagalan: regulasi diabaikan, masa depan digadaikan, dan pendidikan diperlakukan sebagai angka statistik belaka.
Itulah kegelisahan yang mengemuka ketika kebijakan pendidikan dan anggaran kemiskinan dipersoalkan, sementara anak-anak yang telah menempuh tiga tahun masa sekolah justru dihadapkan pada realitas pahit—ijazah paket, bukan pengakuan formal sebagaimana mestinya.
Ibu, Kekuasaan, dan Kemiskinan yang Dipolitisasi
Kemiskinan sejatinya bukan identitas yang layak dieksploitasi. Ia adalah tantangan moral bagi penguasa: mampukah negara membangun kemandirian, atau justru menjadikan kemiskinan sebagai komoditas politik.
Dalam catatan ini, sosok “ibu” hadir sebagai alegori penguasa yang memilih arogansi ketimbang empati. Regulasi dipandang sebagai penghambat, bukan pagar keadilan. Padahal, hukum dan kebijakan publik dirancang untuk melindungi hak paling dasar—termasuk hak anak atas pendidikan yang layak dan diakui negara.
Ketika Regulasi Dianggap Musuh
Alih-alih membuka ruang dialog, kritik justru dibalas dengan kemarahan. Pertanyaan publik dianggap ancaman, bukan peringatan. Sikap ini mencerminkan ketidakdewasaan dalam berkuasa: elektabilitas dikejar tanpa fondasi kredibilitas, popularitas dirawat tanpa integritas.
Dalam konteks pendidikan, pengabaian regulasi berujung fatal. Anak-anak yang telah menempuh proses belajar bertahun-tahun kehilangan pengakuan formal. Ijazah paket menjadi simbol kegagalan sistem, bukan kesalahan peserta didik.
Anak yang Kehilangan, Bukan Secara Fisik
“Di sini saya sebagai anak,” demikian suara batin yang muncul. Kehilangan ini bukan karena kematian, melainkan karena pengkhianatan nilai. Tidak masuk akal jika seorang ibu—atau penguasa—menggadaikan masa depan anak-anak demi citra politik dan keuntungan sempit bagi lingkar kekuasaan.
Kegelisahan ini menemukan bentuk paling nyata pada anak-anak di Norgia: tiga tahun bersekolah, namun tak memperoleh ijazah formal. Sebuah ironi yang pernah diucapkan ahli hukum dari negeri sepak bola, kini menjelma kenyataan yang menyesakkan.
Peringatan Moral bagi Penguasa
Catatan sastra ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan peringatan moral. Regulasi bukan musuh, kritik bukan ancaman, dan anak-anak bukan korban yang bisa dinegosiasikan. Ketika penguasa membenci aturan, yang hancur bukan hanya sistem—melainkan masa depan generasi.
“Pendidikan bukan proyek elektoral. Ia adalah janji negara kepada anak-anaknya,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik yang menolak disebutkan namanya.***