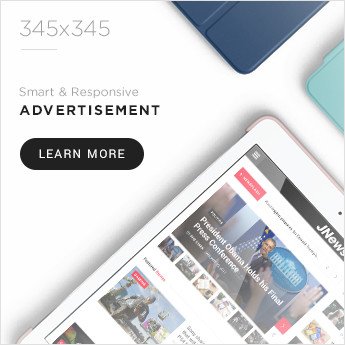SAIBETIK- Puisi Meniti Anak-Anak Bapak merupakan karya yang bertumpu pada kritik sosial-linguistik: penyair menyoroti kegagalan manusia dalam menggunakan bahasa secara utuh sehingga menimbulkan salah paham, kerancuan makna, bahkan konflik relasi.
Tema ini tergolong menarik karena jarang diangkat secara eksplisit dalam puisi; bahasa biasanya menjadi medium puisi, tetapi di sini justru dijadikan objek kritik.
Meniti Anak-Anak Bapak
Kata enggak boleh berpisah,
wajib terjaga layaknya
kupu-kupu dengan bunga
atau sesederhana gelas dan air
Jangankan dokter, suatu kasus
akan sulit pecah dengan kata
yang berpisah
Kita pun sering melihat rumah
tangga yang terpisah. Untuk
menuju kasih sayang ibu,
kadang anak harus bersusah
payak meniti anak-anak bapak
dan berlaku sebaliknya
Jujur saya geram mendengar
dan membaca Anda berkalimat
Seperti beternak kupu-kupu
tapi benci menanam bunga
dan layaknya memberi gelas
tanpa pelengkap
2026
Premis Filosofis Bahasa Ideal
Sejak bait awal, penyair langsung menegaskan tesisnya melalui larik “Kata enggak boleh berpisah, wajib terjaga”. Pernyataan ini berfungsi sebagai premis filosofis bahwa bahasa ideal adalah bahasa yang utuh, selaras, dan tidak tercerai.
Metafora kupu-kupu dengan bunga serta gelas dan air memperkuat gagasan keterikatan alami: ada unsur-unsur yang memang ditakdirkan saling melengkapi. Simbol ini efektif karena sederhana namun mudah divisualisasikan, sehingga pembaca cepat memahami pesan moral tentang pentingnya kelengkapan tuturan.
Cermin Ketidakteraturan Relasi Sosial
Pada bagian tengah, puisi bergeser dari metafora alam ke ranah sosial melalui gambaran rumah tangga yang terpisah. Peralihan ini memperluas makna: keterpisahan kata dianalogikan dengan keterpisahan manusia.
Struktur ini menunjukkan bahwa kekacauan bahasa bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan cermin ketidakteraturan relasi sosial. Frasa “meniti anak-anak bapak” menghadirkan ironi sekaligus absurditas, seolah bahasa yang tidak lengkap memaksa seseorang berjalan di atas struktur makna yang rapuh.
Transformasi Suara Lirik dari Pengamat Jadi Pengkritik
Klimaks puisi muncul di bagian akhir ketika penyair menggunakan nada langsung dan emosional: “Jujur saya geram…”. Pergeseran dari metaforis ke deklaratif ini menandai transformasi suara lirik—dari pengamat menjadi pengkritik.
Dua metafora penutup, beternak kupu-kupu tapi benci menanam bunga dan memberi gelas tanpa pelengkap, merupakan alegori kuat tentang kontradiksi perilaku berbahasa: orang ingin dipahami tetapi enggan menyampaikan maksud secara utuh. Penutup ini efektif karena menyatukan seluruh simbol sebelumnya dalam satu kesimpulan moral.
Fragmentaris Alur Asosiasi Metafora
Secara stilistika, puisi ini mengandalkan diksi sederhana dan struktur bebas tanpa rima tetap. Kesederhanaan tersebut mendukung tema karena kritik terhadap bahasa justru disampaikan dengan bahasa yang lugas.
Namun, transisi antarbaris kadang terasa fragmentaris sehingga alur asosiasi metafora tidak selalu mulus. Jika kesinambungan citraan diperhalus, daya sugestif puisi akan meningkat dan pesan moral dapat mengalir lebih kuat.
Fondasi Relasi Manusia
Secara keseluruhan, puisi ini berhasil menyampaikan kritik tajam terhadap kebiasaan berbahasa yang tidak lengkap atau ambigu. Ia menempatkan bahasa sebagai fondasi relasi manusia dan menegaskan bahwa ketidakutuhan ujaran dapat berujung pada keretakan pemahaman.
Dengan gagasan konseptual yang kuat dan metafora simbolik yang konsisten, karya ini menunjukkan potensi besar sebagai puisi reflektif yang tidak hanya estetis, tetapi juga edukatif.
Penilaian kritis: puisi ini menonjol pada gagasan dan simbolisme, serta efektif sebagai puisi pesan moral, meskipun masih dapat diperkaya dalam kesinambungan struktur imaji agar dampak artistiknya semakin mendalam.***