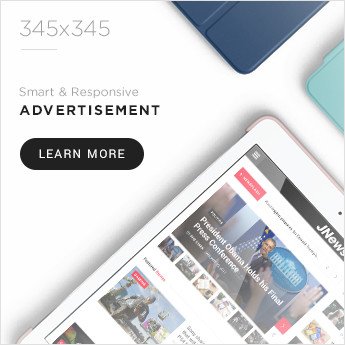SAIBETIK- Puisi “Tukang Bunuh Orang” Karya Muhammad Alfariezie menghadirkan kisah sederhana tentang rumah tua yang direnovasi, hujan yang datang tiba-tiba, dan kelalaian teknis yang nyaris berujung maut.
Namun kesederhanaan ini justru membuka ruang tafsir politis yang relevan dengan dinamika kebijakan publik, khususnya dalam konteks pendidikan.
Ketika dibaca berdampingan dengan kebijakan SMA Swasta Siger di Bandar Lampung, puisi ini bekerja sebagai alegori tentang kekuasaan, kepercayaan, dan risiko yang dipindahkan kepada warga.
Tukang Bunuh Orang
Itu bocor, rumah tua yang baru
pemiliknya renovasi. Tukangnya
kerja cepat, meski tak selincah
kilat. Mungkin karena selesainya
siang awan mantab terpandang,
jadi ia sama sekali tidak curiga
Tapi kemarau masih jauh. Hanya
satu hari, hujan kemudian datang
sejak siang. Karena sibuk untuk
senang sampai bintang, hanya ia
tampung tetes hujan yang melubangi
plafon dengan baskom cuci tangan
Ketika pulang, dia kaget air keluar
pintu. Karena lepas sepatu,
akhirnya tersetrum sampai hampir
mutung
Untung saya tetangga yang tanggap.
Mendengar bantingan pintu, sekedip
pandang– listrik saya minta padam
2026
Rumah Tua dan Janji Renovasi
Rumah tua dalam puisi dapat dibaca sebagai sistem pendidikan yang telah lama berdiri dengan segala keterbatasannya. Renovasi menandai niat baik: pembaruan, inovasi, dan upaya menjawab kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, kebijakan SMA Swasta Siger dapat dipahami sebagai proyek “perbaikan” yang diklaim sebagai solusi—sebuah upaya cepat untuk menambal kekurangan daya tampung atau ketimpangan akses.
Namun puisi ini sejak awal memberi peringatan: renovasi yang dikerjakan terburu-buru, tanpa pengawasan memadai, justru menyisakan kebocoran struktural.
Tukang sebagai Orang Kepercayaan Kebijakan
Figur tukang dalam puisi bukan sekadar pekerja fisik, melainkan simbol pelaksana kebijakan—entah itu tim teknis, konsultan, atau mekanisme administratif yang dipercaya penuh oleh pengambil keputusan. Ia “kerja cepat”, sebuah frasa yang dalam bahasa politik sering dipuji sebagai efisiensi, tetapi dalam puisi ini mengandung ironi: cepat tidak selalu berarti tepat.
Kebijakan pendidikan yang diluncurkan tanpa kesiapan infrastruktur, kejelasan regulasi, atau perlindungan bagi peserta didik dan sekolah swasta, berpotensi menciptakan “plafon bocor”—masalah laten yang baru terasa ketika tekanan datang.
Hujan sebagai Realitas Sosial
Hujan dalam puisi bukan anomali. Ia pasti datang. Dalam kebijakan pendidikan, hujan adalah realitas sosial: keterbatasan ekonomi orang tua, ketimpangan mutu sekolah, kecemasan siswa, dan ketidakpastian masa depan. Puisi ini menegaskan bahwa masalah bukan pada hujannya, melainkan pada sistem yang tidak siap menampungnya.
Ketika kebijakan seperti SMA Swasta Siger diperkenalkan tanpa skema mitigasi yang jelas, risiko tidak hilang—ia hanya dipindahkan. Seperti air yang ditadah baskom, masalah ditahan sementara, bukan diselesaikan.
Sengatan Listrik: Dampak yang Nyaris Mematikan
Pertemuan air dan listrik adalah momen paling politis dalam puisi. Ia melambangkan pertemuan antara kebijakan yang rapuh dan realitas yang keras. Dampaknya tidak abstrak: ia menyengat tubuh, mengejutkan, dan nyaris membunuh.
Dalam konteks pendidikan, “sengatan” ini bisa dibaca sebagai dampak kebijakan terhadap siswa, guru, dan sekolah: kebingungan administratif, beban biaya, hilangnya rasa aman, atau terpinggirkannya sekolah swasta yang tidak siap dijadikan instrumen kebijakan publik tanpa dukungan memadai.
Puisi ini penting karena tidak menggambarkan kematian, melainkan nyaris mati. Sebuah peringatan bahwa bahaya sudah sangat dekat.
Tetangga dan Peran Warga
Bagian akhir puisi menghadirkan “saya tetangga yang tanggap”. Dalam pembacaan politis, tetangga adalah masyarakat: orang tua, guru, pengelola sekolah, dan warga kota yang bersuara. Keselamatan datang bukan dari sistem yang dirancang, melainkan dari intervensi warga yang menyadari bahaya dan bertindak.
Namun kata “untung” mengandung kritik tajam. Keselamatan bergantung pada keberuntungan, bukan jaminan kebijakan. Dalam negara yang sehat, pendidikan tidak boleh bergantung pada “untung-untungan”.
Agitasi Politik yang Sunyi
Puisi “Tukang Bunuh Orang” tidak menyerukan penolakan eksplisit, tetapi mengagitasi kesadaran pembaca: bahwa kebijakan yang tampak baik bisa menjadi berbahaya jika dibangun di atas kepercayaan buta dan kecepatan semu. Dalam kaitannya dengan SMA Swasta Siger, puisi ini mengajak kita bertanya: apakah kebijakan ini benar-benar memperbaiki struktur, atau hanya menambal kebocoran sambil berharap hujan tidak deras?
Sebagai kritik sastra, puisi ini berfungsi sebagai cermin etis bagi kekuasaan lokal. Ia mengingatkan bahwa dalam urusan pendidikan, kelalaian bukan sekadar kesalahan teknis—ia adalah bentuk kekerasan yang paling sunyi.***