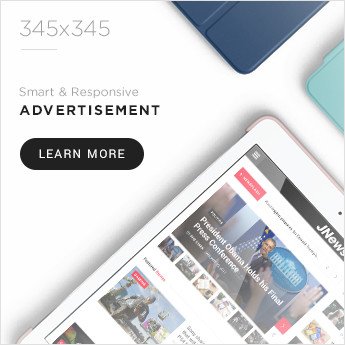SAIBETIK- Prinsip bahwa semua orang sama di mata hukum tampaknya tidak berlaku dalam kisah PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Perusahaan daerah ini terjerat kasus pengelolaan dana bagi hasil migas atau Participating Interest (PI) 10% yang justru membuat publik bertanya-tanya. Sebab, di provinsi lain, mekanisme yang sama berjalan tanpa hambatan dan bahkan dipuji sebagai praktik tata kelola BUMD yang baik.
Langkah Kejati Lampung dalam memproses jajaran direksi dan komisaris PT LEB dinilai sebagai bentuk penegakan hukum yang ingin dijadikan percontohan nasional. Namun percontohan seperti apa, jika hasilnya justru menimbulkan ketidakadilan? Pertanyaan ini menggema di tengah suasana politik Lampung yang memanas kala itu, menimbulkan dugaan bahwa kasus hukum ini tidak sepenuhnya murni.
Ketimpangan Hukum yang Mencolok
Di Indonesia, setidaknya ada tiga BUMD yang menerima dan mengelola dana PI 10% migas seperti PT LEB, yaitu di Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Ketiganya memiliki struktur hukum dan pola kerja yang sama: ditunjuk oleh SKK Migas sebagai penerima PI, menerima dana dari Pertamina Hulu, lalu membagikan dividen kepada pemerintah daerah melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua diaudit oleh lembaga resmi, dan tidak ada yang dianggap melanggar hukum.
Namun ironisnya, ketika Lampung melakukan hal yang sama, hasilnya justru berbeda. PT LEB dianggap melakukan pelanggaran. Padahal dalam konteks hukum korporasi, dana PI adalah pendapatan perusahaan, bukan dana publik yang harus langsung masuk ke kas daerah. Perbedaan tafsir inilah yang menjadi titik krusial dan menimbulkan dugaan adanya bias dalam penerapan hukum.
Mengapa di Riau, Jawa Barat, dan Kaltim dana PI dianggap wajar sebagai laba BUMD, sementara di Lampung justru dijadikan dasar penyidikan korupsi? Apakah karena waktunya bertepatan dengan tahun politik dan tarik-menarik kekuasaan di daerah?
Studi Kasus I: Riau Petroleum, BUMD yang Aman dan Dipuji
PT Riau Petroleum, yang menjadi penerima PI 10% untuk Wilayah Kerja Rokan, menjalankan mekanisme yang sama seperti PT LEB. Dana diterima dari Pertamina Hulu Rokan (PHR) ke rekening perusahaan, lalu dibagi dalam bentuk dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui RUPS. Audit dilakukan oleh BPKP dan kantor akuntan publik independen.
Tidak ada dana yang langsung disetor ke kas daerah. Semua masuk ke pembukuan perusahaan, diakui sebagai pendapatan korporasi. Pemerintah daerah hanya menerima dividen sesuai keputusan RUPS. Sistem ini dianggap sah, transparan, dan efisien. Hingga kini, tidak pernah muncul kasus hukum. Artinya, hukum memahami bahwa dana PI adalah bagian dari kegiatan bisnis, bukan uang negara dalam arti keuangan publik.
Studi Kasus II: Migas Hulu Jabar ONWJ, Transparan dan Profesional
PT Migas Hulu Jabar (MUJ ONWJ) di Jawa Barat juga memiliki pola identik. Berdiri atas dasar keputusan Gubernur Jawa Barat dan disetujui SKK Migas, perusahaan ini menjadi penerima PI 10% untuk wilayah kerja Offshore North West Java. Pendapatan diperoleh dari Pertamina Hulu Energi ONWJ dan dikelola sebagai laba perusahaan.
Pembagian dividen dilakukan melalui BUMD induk dan disahkan lewat RUPS. Semua laporan keuangan diaudit dan dilaporkan secara terbuka. Tidak ada intervensi, tidak ada kasus hukum. Pemerintah daerah Jawa Barat justru menjadikan MUJ ONWJ sebagai contoh keberhasilan BUMD migas yang transparan dan akuntabel.
Studi Kasus III: Migas Mandiri Pratama Kutai Timur, Dapat Penghargaan Bukan Jeratan
PT Migas Mandiri Pratama Kutai Timur (MMP-KT) adalah contoh lain bahwa hukum bisa berpihak jika diterapkan dengan benar. Berdasarkan surat Dirjen Migas, perusahaan ini menjadi penerima PI 10% Wilayah Kerja Mahakam dan menerima dana dari Total E&P dan Pertamina Hulu Mahakam.
Laba bersih dibagikan kepada pemerintah daerah lewat RUPS, sisanya digunakan untuk operasional dan pengembangan usaha. Tidak hanya bebas dari masalah hukum, MMP-KT justru mendapatkan penghargaan dari SKK Migas atas kepatuhan dan tata kelola yang baik.
Lampung: Dari Korporasi ke Kambing Hitam
Melihat ketiga contoh tersebut, muncul ironi besar. Pola hukum dan akuntansi mereka identik dengan PT LEB. Namun, hanya Lampung yang dijadikan tersangka dalam tafsir hukum yang tiba-tiba berubah arah.
PT LEB bahkan tidak bekerja sendiri. Dana PI 10% dikelola bersama BUMD DKI Jakarta dengan porsi 5% untuk masing-masing pihak. Namun entah mengapa, hanya pihak Lampung yang terseret kasus. Apakah ini kebetulan, atau ada motif yang lebih dalam dari sekadar kesalahan administratif?
Kasus ini membuat publik semakin skeptis. Banyak yang menilai, Lampung dijadikan “kelinci percobaan” dalam uji tafsir hukum dana migas. Ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan alat politik, maka wajar jika kepercayaan publik ikut luntur.
Refleksi: Di Mana Keadilan untuk Lampung?
Dari sudut pandang hukum tata kelola migas, mekanisme PI 10% diatur jelas dalam regulasi SKK Migas dan peraturan Kementerian ESDM. Artinya, semua BUMD penerima PI tunduk pada aturan yang sama. Namun ketika satu daerah dipidana dan daerah lain dipuji, keadilan menjadi kabur.
Apakah aparat hukum di Lampung salah menafsirkan batas antara keuangan publik dan keuangan korporasi? Atau justru ada kekuatan politik yang memanfaatkan hukum sebagai senjata?
Pada akhirnya, kasus ini menjadi simbol dari persoalan lebih besar: bahwa penegakan hukum di Indonesia masih rentan terhadap tafsir, intervensi, dan kepentingan. Lampung mungkin hanyalah satu kasus dari sekian banyak yang menggambarkan betapa “hukum yang sama” bisa menghasilkan nasib yang sangat berbeda.
Dan kini, masyarakat hanya bisa berharap, keadilan bukan sekadar jargon di ruang sidang—tetapi benar-benar hadir bagi setiap daerah, termasuk Lampung, yang hanya ingin memperjuangkan haknya dalam pengelolaan kekayaan alam sendiri.***