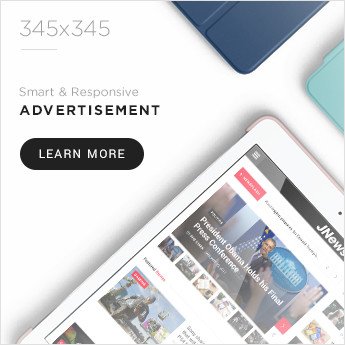SAIBETIK – Sebuah diskusi sastra menggelorakan semangat literasi di FKIP Universitas Lampung (Unila) pada Rabu, 1 Oktober 2025. Diskusi Buku Sastra #1 ini menghadirkan puisi Ari Pahala Hutabarat dalam karya terbarunya, *Hari-Hari Bahagia* (Lampung Literature, 2023), yang memicu perbincangan mendalam tentang makna kebahagiaan, spiritualitas, dan estetika dalam puisi.
Ari Pahala Hutabarat, penyair nasional asal Lampung sekaligus sutradara teater di Komunitas Berkat Yakin (KoBER), mengaku kembali ke kampusnya setelah 35 tahun meninggalkan FKIP Unila. “Selama ini saya belum pernah ke FKIP sebagai penyair. Rupanya harus 35 tahun dulu baru kembali,” ungkap Ari Pahala di hadapan peserta. Ari merupakan satu-satunya penyair Indonesia yang lahir dari FKIP Unila, menempuh S1 dan S2 pada Prodi Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Diskusi ini juga menghadirkan Dr. Munaris, M.Pd., Ketua Prodi Bahasa Lampung FKIP Unila, dan Iswadi Pratama, penyair sekaligus sutradara Teater Satu lulusan FISIP Unila. Kegiatan ini dimoderatori oleh Edi Siswanto, M.Pd., dan terselenggara berkat dukungan Kemdikbud RI melalui program Penguatan Komunitas Sastra.
Membongkar Mitos Kebahagiaan
Iswadi Pratama memaparkan 12 halaman analisis tentang tiga puisi pilihan dalam buku Hari-Hari Bahagia. Ia menekankan bahwa Ari Pahala memulai perjalanan kreatifnya dari ruang spiritual—hening, transenden, dan sarat simbolisme. “Meminjam pandangan Simone Weil, puisi ini sebagai decreation, pengosongan diri. Sepi ungu dan hati biru adalah tanda jiwa melepaskan ego, menunduk, dan terbuka pada yang Ilahi,” jelas Iswadi.
Menurut Iswadi, puisi-puisi Ari bukan sekadar ekspresi romantis, tetapi doa dan ratapan seorang mistikus. Misalnya, puisi *aku akan pergi, katamu* menampilkan cinta yang melampaui hubungan manusia, menyentuh ranah spiritual. Dengan strategi naratif yang cermat, Ari berhasil membuat puisi bersifat universal namun tetap kontekstual, menghadirkan tokoh dan fenomena sosial seperti tubuh boyak atau politikus korup dengan nuansa paradoksal dan humor gelap.
“Mitos kebahagiaan yang sering dipuja dalam tradisi romantik dijatuhkan ke tong sampah. Kebahagiaan Ari bukan megah, tapi sederhana bahkan absurd. Di situlah ketajaman puisinya: meski hidup grotesque, tetap pantas dijalani, bahkan ditertawai,” tegas Iswadi Pratama.
Klimaks Penyair Ada di Puisinya
Sebelumnya, Dr. Munaris menekankan bahwa klimaks seorang penyair berada pada puisi-puisinya, bukan pada kehidupan pribadi. “Kalau sehari-hari penyair tampak biasa, itu sudah tumpah dalam puisi-puisinya,” ujarnya. Munaris menyoroti diksi Ari yang kaya warna—ungu, biru, hijau, merah, putih—yang menjadikan kata biasa sebagai medium ekspresi artistik penuh daya sugesti. Diksi tersebut memperkuat efek emosional, memperdalam citraan, dan menambah makna yang tidak selalu bisa dijelaskan secara langsung.
Menurut Munaris, diksi puisi tidak hanya alat komunikasi, tetapi medium estetik yang memadukan rasa, irama, simbol, dan keindahan bunyi. Hal ini menjadikan Hari-Hari Bahagia bukan sekadar buku puisi, melainkan pengalaman estetik yang memikat dan merangsang refleksi pembaca.
Diskusi yang hangat ini menegaskan pentingnya pengembangan komunitas sastra di Lampung, sekaligus menunjukkan bagaimana puisi bisa menjadi sarana memahami kehidupan, spiritualitas, dan realitas sosial secara mendalam.***