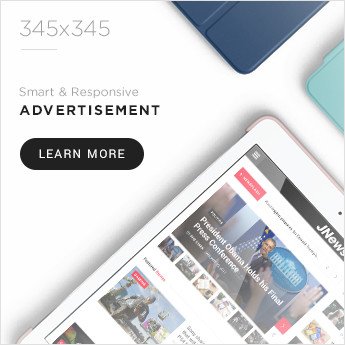SAIBETIK- Puisi “Malam Menyulam Perpisahan” karya Muhammad Alfariezie mulai ramai dibahas karena vibes-nya yang halus tapi nyelekit, relatable tapi penuh misteri. Dari piama sampai kunang-kunang, setiap detail dalam puisi ini terasa seperti simbol yang sengaja dibiarkan mengambang—enggak pernah fix maknanya, tapi justru di situlah letak magisnya.
Puisi ini kerjanya bukan menjelaskan, tapi memancing emosi. Bukan menggurui, tapi membiarkan pembaca menemukan luka dan rindunya sendiri di antara jeda-jedanya. Bacaan yang kelihatan sederhana, tapi efek psikologisnya bisa bikin pembaca tiba-tiba mikirin “si dia” jam 1 pagi.
Puisi yang Bernafas Lewat Simbol: Piama, Wedang, Hujan, dan Kenangan
Alfariezie menaburkan citraan-citraan domestik—piama merah jambu, benang rajut, wedang, hujan, kunang-kunang—yang semuanya terasa dekat dengan keseharian. Tapi dalam pendekatan poststrukturalisme, simbol-simbol ini bukan sekadar ornamen; mereka adalah penanda cair alias makna yang bisa berubah-ubah tergantung siapa yang membaca.
Di tangan Alfariezie, objek-objek itu jadi kayak “kode rahasia perasaan”:
- wedang = kehangatan yang sudah mulai retak
- benang = hubungan yang masih dicoba untuk dipertahankan
- hujan = kesedihan yang ditunda
- kunang-kunang = harapan kecil yang tetap nyala di tengah gelap
Ambiguitasnya rapi dan sengaja. Seakan penyair ingin pembaca ikut menafsir—bukan sekadar menerima.
Versi Full Puisi “Malam Menyulam Perpisahan”
(Disertakan utuh untuk pembacaan mendalam)
Mengenakan piama merah jambu
penghibur pandang menjelang
bulan berbinar, nyonya duduk tenang
sambil merajut benang menunggu tuan
dari menjual hasil ladang
Saya dipanggilnya untuk mengantar
segelas wedang. Sambil mereguk
yang saya letakkan di meja kemudian
dia berkata
“Sudah lama kamu tidak pulang,
enggak rindu pelukan?”
Nyonya adalah peramal jitu
menebak perasaan. Sudah lama
saya termenung dari balik kaca
untuk sekadar menghitung
berapa lama hujan bertahan
Kini tiba untuk saya berucap
“Iya nyonya, sudah lama saya
berharap kembang memekarkan
ranum dan menebar harum”
Malam kian terasa seperti
perjalanan laut dan darat. Dalam
haru terang kunang-kunang. Saya
bingung besok harus bagaimana
memulai perpisahan setelah tadi nona
berkata
“Tunaikan yang harus segera tunai”
2025
Dibaca dari Kacamata New Lyric Criticism: Suara Liris yang Lagi Patah Tapi Tetap Elegan
Dalam teori kritik sastra modern, puisi kayak gini bukan cuma rangkaian kata, tapi “ruang batin”. Suara “saya” adalah pusat tegangan emosional—seseorang yang sedang berada di tengah antara rindu, kewajiban, dan perpisahan yang enggak diucapkan berulang kali tapi terasa sepanjang puisi.
- “Mengenakan piama merah jambu…” membuka suasana manis tapi janggal.
- Nyonya tampil sebagai figur rumah: lembut, familiar, tapi bikin “saya” dihadapkan pada pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari.
- Setiap adegan terasa seperti jeda hening dalam film yang intim.
Suara dalam puisi ini pelan, tenang, tapi penuh tekanan—kayak seseorang yang sudah menyiapkan kalimat perpisahan tapi belum sanggup melafalkan.
Afek yang Menohok: Emosi yang Tidak Diucapkan Tapi Dirasakan
Dalam pendekatan afektif, puisi ini bekerja seperti denyut pelan yang makin lama makin terasa.
Ada:
- rindu yang tertahan,
- keputusan yang belum diambil,
- dan perpisahan yang makin dekat tapi belum diumumkan.
Emosi tidak disajikan langsung, tetapi lewat benda-benda kecil:
- benang yang dirajut (hubungan yang dirapikan kembali)
- hujan yang dihitung (penantian yang panjang dan melelahkan)
- kembang yang belum mekar (harapan yang tertunda)
Efeknya? Pembaca merasa “terlibat”, meski enggak ada satu pun emosi yang diungkapkan secara frontal.
Makna yang Bergerak: Poststrukturalisme Mode On
Tokoh-tokohnya—nyonya, saya, nona—semua adalah tanda yang tidak pernah fix:
- Nyonya bisa jadi ibu, rumah, masa lalu, atau bahkan keteduhan yang sebentar lagi hilang.
- Saya adalah subjek yang kehilangan pegangan: perantau, kekasih, atau seseorang yang siap meninggalkan zona nyaman.
- Nona adalah masa depan, tuntutan, atau suara hati yang mengajak beranjak.
Kalimat pamungkas “Tunaikan yang harus segera tunai” sengaja dibiarkan terbuka.
Itu bisa berarti:
- pulang,
- pergi,
- mengakhiri hubungan,
- atau menyelesaikan luka.
Semua makna valid, semua makna hidup.
Tema Utama: Perpisahan yang Tidak Diumumkan, Tapi Disulam Perlahan
Puisi ini enggak menjadikan perpisahan sebagai momen dramatis, melainkan proses yang tenang tapi menekan. Perpisahan digambarkan seperti:
- hujan yang lama
- perjalanan darat dan laut
- benang yang dirajut
- kembang yang belum mekar
Bukan sekali putus.
Tapi mengendap, lama, perlahan: perpisahan sebagai proses emosional, bukan klimaks.
Diksi yang Bikin Dekat: Sederhana Tapi dalam
Penggunaan bahasa sehari-hari—piama, wedang, pelukan—membuat puisi terasa dekat, kayak percakapan orang rumah. Tapi justru kesederhanaan ini jadi strategi estetis yang kuat.
Di sinilah genius Alfariezie:
kata-kata sederhana, tapi resonansinya kompleks.
Bukan puisi yang ribut, tapi puisi yang “diam dan menyentuh”.
Kesimpulan: Puisi yang Tenang di Permukaan, Tapi Ramai di Batin
“Malam Menyulam Perpisahan” adalah puisi yang:
- lembut,
- ambigu,
- emosional,
- dan penuh ruang kosong yang mengundang pembaca masuk.
Ia tidak menjelaskan perasaan—ia memantulkan perasaan pembacanya sendiri.
Dan di era Gen Z dan milenial yang hidup dengan perasaan yang sering tidak selesai, puisi seperti ini terasa sangat relevan: tenang, tapi penuh resonansi.***