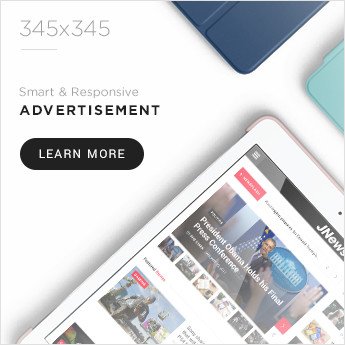Oleh M. Iqbal Farochi, Mahasiswa Magister UNJ
SAIBETIK– Drama hukum Indonesia kembali mencuri perhatian publik. Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan OJK menjadi sorotan utama, bukan hanya karena nominalnya yang fantastis, tetapi juga cara “pertunjukan” yang berjalan seolah sudah diatur skripnya. Alur cerita lengkap dengan pemeran utama yang masih berkeliaran bebas ini membuat publik bertanya-tanya: siapa yang benar-benar bertanggung jawab?
Tersangka kasus ini, anggota DPR RI Komisi XI Satori dan Heri Gunawan, hingga kini belum ditahan. Publik mempertanyakan logika di balik penanganan kasus ini. Bagaimana mungkin dana puluhan miliar yang berasal dari lembaga keuangan sekelas BI dan OJK bisa dicairkan dan digunakan tanpa pengawasan ketat, sementara penegak hukum tampak menunggu momentum tertentu untuk bertindak?
Panggung Komisi XI DPR RI menjadi pusat perhatian. Meski dana CSR seharusnya disalurkan melalui mekanisme kolektif, hanya dua orang yang menjadi tersangka. Sementara anggota komisi lainnya tetap “malaikat” yang menolak godaan dana berkah, seolah memperlihatkan integritas yang kokoh di tengah badai skandal.
Proses pemeriksaan yang lambat dan selektif ini dinilai publik bukan sekadar ketidaktepatan, tetapi strategi. Ada dugaan penegak hukum menunggu waktu yang tepat, entah pasca reses, menjelang Pilkada, atau saat situasi politik lebih stabil, untuk memeriksa anggota DPR lainnya. Sementara itu, dua tersangka utama menjadi sorotan kamera, menampilkan drama hukum yang terlihat “ramah” bagi elite politik.
Yang menarik, kasus ini memperlihatkan dinamika hubungan legislatif dan regulator. Gubernur BI dan pejabat OJK tetap terlihat terhormat, seolah urusan dana puluhan miliar hanyalah “receh” yang bisa diatur oleh mekanisme internal tanpa mengganggu stabilitas lembaga. Publik menilai, ada semacam “gotong royong” elite di balik layar yang menjaga keharmonisan sambil tetap mengamankan kepentingan pribadi.
Dari perspektif masyarakat, kasus CSR ini mengajarkan bahwa korupsi di Indonesia kini seperti seni pertunjukan: Penegak hukum, pejabat negara, dan anggota legislatif menjalankan peran masing-masing, sementara dana rakyat menjadi “pelumas” hubungan antar elite. Bukan sekadar penyalahgunaan, tetapi drama kompleks yang mencerminkan bagaimana kekuasaan, uang, dan integritas berjalan berdampingan dalam bingkai politik nasional.
Selain itu, kasus ini membuka pertanyaan penting soal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana CSR di lembaga publik. Publik menuntut agar penegak hukum tidak berhenti pada dua tersangka saja, melainkan melakukan investigasi menyeluruh agar semua pihak yang terlibat bisa dipertanggungjawabkan.
Sistem hukum Indonesia, meski sering dikritik karena lambat dan selektif, tetap menjadi ujian bagi masyarakat sipil. Peran media, akademisi, dan penggiat anti-korupsi menjadi vital untuk memastikan cerita ini tidak berhenti hanya sebagai panggung sandiwara. Dana rakyat harus terlindungi, dan konsep “berkah” dalam CSR harus kembali ke tujuan awalnya: Membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, bukan menjadi alat politik atau pelumas hubungan elite.***