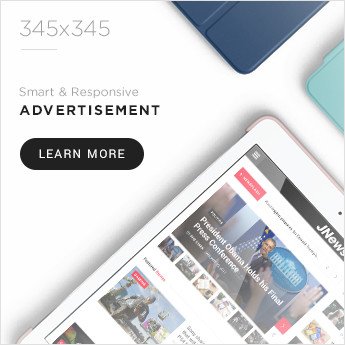SAIBETIK— Pada Sabtu yang basah oleh rintik dan langit mendung, puisi tak kehilangan panggungnya. Di Plaza Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Hari Puisi Indonesia (HPI) ke-13 dirayakan secara terbuka, menghadirkan suara-suara yang biasanya hanya bergema di ruang-ruang sastra.
Di antara deretan pembaca puisi, nama Andria C. Tamsin mencuat bukan karena volume suara, melainkan karena kedalaman penghayatan. Ia datang dari Padang, Sumatera Barat, membawa puisi sebagaimana seorang musafir membawa doa dalam perjalanan panjang.
Ie—begitu ia disapa akrab—bukan wajah baru dalam jagat puisi Indonesia. Peraih penghargaan pembaca puisi terbaik dalam lomba H.B. Jassin tahun 1994, Andria adalah bukti bahwa puisi tidak hanya lahir dari pena, tapi juga dari kesetiaan bertahun-tahun dalam membaca, mendalami, dan mempersembahkan.
“Puisi sudah menyatu dengan kehidupan saya,” katanya, usai membacakan puisi karya Hamid Jabbar yang mengguncang kesadaran: Puisi Komputer Teler.
“Kalian jejalkan data data data…”
“Aku bilang kalian dusta dusta dusta…”
Andria tak membacakan puisi itu seperti penghafal. Ia menjadi puisi itu sendiri—dengan sorot mata, nada suara, dan jeda yang dipilih dengan kepekaan batin, bukan teknis.
Penonton terdiam, nyaris tak ada gerakan selain mata yang menatap dan telinga yang mendengar. Panggung terbuka yang semula bising oleh angin dan rintik hujan berubah menjadi ruang khidmat.
Andria bukan hanya seorang dosen Universitas Negeri Padang. Ia juga penyaksi hidup dari persetubuhan antara akademik dan seni, antara akal dan rasa. Ia mengaku tak bisa memilih hanya satu. “Mengajar dan membaca puisi adalah dua sisi dari satu hidup,” tuturnya.
Ia pernah membawa puisinya ke Timur Tengah, menyusuri Mesir, hingga akhirnya sujud di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bagi Andria, puisi bukan sekadar seni ekspresi, melainkan jembatan spiritual menuju Tuhan.
“Saya cukup disebut pembaca puisi terbaik. Gelar ‘sang juara’ masih terlalu tinggi,” ucapnya merendah, walau publik tahu: auranya di atas panggung tak pernah berbohong.
Ia bahkan bermimpi, saat kelak dikukuhkan sebagai Profesor, ingin perayaan itu diisi oleh pembacaan puisi dari para penyair terbaik Indonesia. “Saya ingin hari itu jadi hari puisi pribadi saya. Doakan ya, semoga tahun depan,” ujarnya dengan senyum bersahaja.
Dan malam itu, di panggung terbuka Jakarta, suara Andria menembus batas usia, batas ruang, bahkan batas literasi. Ia membuktikan bahwa puisi bukan barang mewah bagi segelintir, melainkan milik siapa saja yang percaya pada kekuatan kata.
Puisi bukan hanya dibaca. Ia dihidupkan. Dan Andria telah melakukannya.***