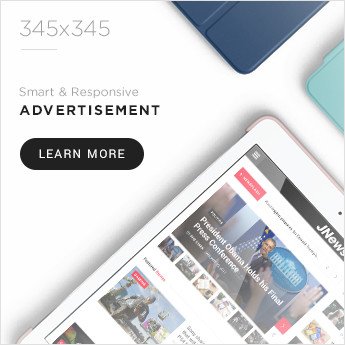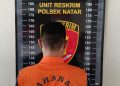SAIBETIK – Keraton Jogjakarta, sebuah landmark tak terbantahkan yang memancarkan kebesaran sejarah dan kekayaan budaya, menjadi perwakilan terkemuka dari identitas Yogyakarta sebagai jantung Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dengan keindahan arsitektur yang khas bagi istana Jawa, Keraton ini dikenal sebagai mahakarya yang tak tertandingi.
Kesakralan dan kemegahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tercermin jelas dalam desainnya yang didominasi oleh warna putih, yang tak hanya menegaskan identitasnya sebagai pusat pemerintahan pada zamannya, tetapi juga mencitrakan keanggunan yang abadi.
Pembangunan megah Keraton Kesultanan Yogyakarta tak lepas dari peristiwa bersejarah, Perjanjian Giyanti tahun 1775, yang membagi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram menjadi dua entitas terpisah: Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dihormati dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I, Keraton Yogyakarta menjadi bukti jelas kepiawaian dalam arsitektur, diakui bahkan oleh Belanda sebagai puncak kegemilangan dengan nuansa Jawa yang agung namun tetap memancarkan kesederhanaan yang elegan.
Terletak di lahan seluas 14 ribu meter persegi, Keraton ini menjulang di antara Kali Code dan Kali Winanga. Awalnya, lahan ini merupakan rawa yang dikenal sebagai Umbul Pachetokan, yang kemudian dikeringkan dan diubah menjadi kompleks istana yang menggabungkan berbagai bangunan fungsional dan halaman yang memukau.
Keraton, dalam arti sejatinya, adalah tempat kediaman para raja, dan juga dikenal dengan sebutan Kadaton atau Kedatuan, yang sama-sama melambangkan tempat kerajaan. Desainnya diatur sedemikian rupa sehingga terletak sejajar dengan Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan, dengan titik pusatnya berada di Sumur Gemuling Taman Sari, tempat di mana Sri Sultan melakukan meditasi dan diyakini sebagai jalan pintas menuju Ratu Laut Kidul.
Keraton yang menghadap ke utara ini terdiri dari berbagai bangunan dengan fungsi berbeda, dengan pusat kegiatan utamanya berada di Pesanggrahan Ayodya. Halaman depan, dikenal sebagai alun-alun utara, menghadap ke utara, sementara alun-alun belakang, dikenal sebagai alun-alun selatan, terletak di bagian belakang.
Dikelilingi oleh tembok selebar 4 meter dengan panjang mencapai 1 kilometer, yang disebut beteng, Keraton ini didesain dengan teliti. Parit yang luas dan dalam melingkupi tembok tersebut, sementara di keempat sudut terdapat bastion yang dilengkapi dengan lubang-lubang kecil untuk pengawasan dan pengintaian.
Bagian dalam Keraton menjadi saksi dari keanggunan dan fungsi yang beragam. Balairung Keraton menjadi tempat bagi persidangan agung, dengan singgasana Sri Sultan yang memimpin, diapit oleh para pejabat istana. Ruang Regol Donopratomo, yang menghubungkan halaman Sri Manganti dengan halaman utama Keraton, dijaga oleh dua patung dwarapala yang mengesankan.
Tempat tinggal Sri Sultan, yang juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan melaksanakan ritual adat, menjadi fokus utama. Sementara itu, di sekitarnya, terdapat keputren-keputren yang menjadi tempat tinggal bagi putra dan putri Keraton.
Bangunan utara Keraton meliputi kedaton, bangsal kencana, Regol Danapratapa, ruang Sri Manganti, Bangsal Ponconiti, Siti Inggil, hingga Pagelaran. Di sisi selatan, terdapat Bangsal Kemagangan, Bangsal Kemandungan, serta Siti Inggil. Ruangan khusus juga disediakan untuk menyimpan benda-benda pusaka milik Sri Sultan.
Ada lima pintu gerbang utama, yang disebut plengkung, yang menghubungkan Keraton dengan dunia luar: Plengkung Tarunasura di timur laut, Plengkung Jogosuro di barat daya, Plengkung Jogoboyo di barat, Plengkung Nirboyo di selatan, dan Plengkung Tambakboyo di timur.
Di masa lampau, bangunan-bangunan dan kampung di sekitar Keraton digunakan sebagai tempat tinggal bagi berbagai abdi dalem, yang tugasnya disesuaikan dengan posisi mereka di dalam hierarki Keraton. Gandekan, misalnya, adalah kampung bagi kurir Keraton, sementara Wirobrajan menjadi tempat tinggal bagi prajurit Wirobrojo, dan Pasindenan diperuntukkan bagi sinden-sinden istana yang mempesona.***